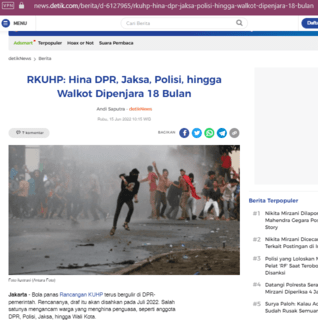mijil.id - Kondisi kebebasan berpendapat, berekspresi, serta demokrasi saat ini menjadi salah satu permasalahan yang tidak banyak kita sadari. Benarkah di masa kini masih ada pembungkaman pendapat di ruang publik? Hmm… bisa saja benar bisa juga tidak.
Sumber gambar: pngwing.com
Apabila kita telisik atau menuju masa orde baru setelah peristiwa Malari banyak sekali pembungkaman media pers yang dilakukan oleh pemimpin pada saat itu, seperti peristiwa pembredelan Majalah Tempo, Editor, dan Tabloid Detik. Namun, setelah masa reformasi kelonggaran kebebasan pers dan berpendapat mulai dapat dirasakan oleh jurnalis Indonesia walaupun masih dalam belenggu kecemasan karena peristiwa pembungkaman pers masa orde baru.
Tapi kita perlu bertanya-tanya apakah di masa demokrasi saat ini masih terdapat pembungkaman pers atau berpendapat? Untuk menjawab hal ini mungkin kita akan beranjak ke tahun 2008 di mana saat Presiden saat itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan sebuah undang-undang yang bernama UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikeluarkan setelah 10 tahun perjuangan reformasi yang memberikan perlindungan kepada warga untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat.
Namun, pada nyatanya UU ITE ibarat dua sisi mata pisau yang mempunyai manfaat dan keburukan bagi kebebasan berpendapat serta dunia jurnalistik. Sebenarnya pemerintah saat itu mempunyai niat yang baik dalam pembuatan UU ITE yaitu sebagai upaya melindungi konsumen saat melakukan transaksi elektronik di tengah masifnya internet pada perekonomian negara. Tentu hal ini akan menjadi upaya melindungi warga negara dalam menggunakan teknologi saat bertransaksi. Tetapi pada penerapannya, pemerintah dan aparat justru terkadang menyalahgunakan UU tersebut untuk membungkam para pihak yang mengkritik negara atau menyampaikan aspirasi.
Sisi lain dari UU ITE adalah penyalahgunaan undang-undang tersebut yang menimbulkan ancaman kemerdekaan pers dan kemerdekaan berekspresi masyarakat. Salah satunya pada Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE yang berpotensi mengebiri pers karena berita pers dalam wujud informasi elektronika (di internet), terkait dengan kasus-kasus korupsi, manipulasi dan sengketa, dapat dinilai sebagai penyebaran pencemaran atau kebencian.
Presiden Jokowi dan anggota DPR juga pernah mengusulkan bahwasannya pasal tersebut perlu dikaji kembali, karena menimbulkan problematika di masyarakat serta dunia pers.
Jika saya mencermati di berita, “korban terakhir” dari UU ITE salah satunya adalah Dandhy Laksono pemilik channel Youtube Watchdoc Documentary, dianggap melakukan ujaran kebencian melalui media elektronik yang dituding melanggar pasa 28 Ayat (2) dan pasal 45A Ayat (2) UU ITE. Tidak hanya itu saja di masa pandemi banyak bermunculam mural-mural yang bertuliskan kritikan. Namun, sesudah viral mural tersebut tiba-tiba dihapus oleh apparat. Hal ini tentunya menjadi sebuah tanda tanya besar apakah kebebasan berpendapat mulai terbungkam saat ini?
Walaupun begitu tentunya kita sebagai warga negara yang baik tau bagaimana menyampaikan sebuah pendapat atau kritikan yang baik tanpa menimbulkan kerusuhan, musuhan, serta ancaman. Begitu juga dengan pemerintah, diharapkan mampu menerima setiap kritikan oleh masyarakat tanpa membungkam ataupun menimbulkan sebuah ancaman.
Pernah saya baca satu buku berjudul A9ama Saya adalah Jurnalisme ditulis oleh Andreas Harsono yang mengatakan “makin bermutu jurnalisme dalam suatu masyarakat, maka makin bermutu pula masyarakat itu”. Better Journalism, Better Lives!
Kata-kata tersebut menjadi sebuah bukti bahwasannya jika kebebasan jurnalistik yang bermutu dan kritis di batasi, semata-mata hanya untuk melindungi pihak terkait saja maka masyarakat akan semakin terjerumus ke jurang kesesatan. Tetapi jika jurnalistik diberikan kebebasan dengan berlandaskan kode etik pers maka masyarakat akan semakin mengerti tentang sebuah kebenaran dan kebohongan dalam kehidupan di masyarakat.
Penulis: Muhammad Aditya Wisnu Wardana